Fiksi
Saat membaca berita tentang penyerangan 75 tentara ke Markas Polres OKU, Sumatera Selatan, 7 Maret 2013, saya membayangkan ia adalah adegan fiksi. Namun, adegan tersebut gagal membuat saya kagum karena fiksi yang sesungguhnya tampaknya lebih menarik. Di film The Expandable, misalnya, aksi Jason Statham dan Sylvester Stallon lebih bisa membuat adrenalin saya terpacu.
Akhir-akhir ini saya memang kerap membayangkan sejumlah kejadian memilukan di negeri ini sebagai sebuah fiksi. Sebagai fiksi, tentu saja ia hanya rekaan pikiran, tak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan. Persis dongeng-dongeng pengantar tidur. Namun, lagi-lagi, dongeng kancil yang mencuri timun masih tampak lebih menarik ketimbang peristiwa-peristiwa tersebut.
Menghadirkannya sebagai fiksi merupakan salah satu upaya menenteramkan hati dari gempuran berita-berita negatif yang diproduksi media setiap hari. Sebagaimana kita tahu, negeri ini dikelola dengan keributan yang sungguh luar biasa. Oleh para penguasa, kita dibuat pusing terhadap berbagai masalah yang tumpang-tindih. Tak usai masalah yang satu, timbul masalah berikutnya. Kasus yang satu diungkap untuk menutupi kasus-kasus lainnya.
Bosan dengan skenario politik yang mudah ditebak, akhirnya saya hanya berharap kepada dunia fiksi. Dunia tersebut menawarkan relaksasi. Ia kadang juga diam-diam membuat saya tersenyum, membayangkan betapa bodohnya saya saat mempercayai omongan politisi yang mengaku agamis, padahal maling.
Di waktu yang lain, Luis Sepulveda, novelis dan jurnalis kelahiran Cile tahun 1949, membawa ingatan saya kepada salah satu adegan dalam novelnya yang berjudul �Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta� (Marjin Kiri, 2005). Dalam novel tersebut digambarkan seorang walikota yang tambun dan malas berpikir. Penduduk El-Idilio menjuluki lelaki tersebut dengan la Babosa, Siput Lendir. Tubuh gempalnya terus memproduksi keringat dan membuat lelaki itu tak lepas dari pekerjaan memeras sapu tangannya.
Suatu ketika, walikota tersebut menuduh sejumlah orang Indian Shuar, penduduk lokal, menghunjamkan parang ke tubuh seorang bule yang datang ke daerah itu, hingga membuatnya tewas dan membusuk. Orang Shuar menolak, namun walikota ngotot dan menghantamkan popor senapannya. Antonio Jose Bolivar Proano, seorang pendatang dari San Luis, sebuah desa dekat gunung api Imbabura, mencoba menentang walikota. �Maaf. Anda omong kosong. Tak ada luka parang,� katanya. �Aku tahu apa yang kulihat,� sergah walikota. �Tidakkah Anda lihat daging terkoyak mengelupas? Tidakkah Anda lihat luka tetak ini dalam di bagian rahang dan makin ke bawah makin dangkal? Tidakkah Anda lihat ada empat sabetan, bukan satu?� lanjut Bolivar. �Apa maksudmu?� tanya walikota. �Tidak ada yang namanya parang empat mata. Ini bekas cakar. Cakar macan kumbang. Hewan yang sudah dewasa benar yang membunuhnya. Enduslah ini,� kata Bolivar.
Gambaran fisik sang walikota yang tambun bisa jadi sebuah simbol penguasa yang lamban. Negeri ini juga pernah menghadirkan sebuah simbol untuk pemerintah karena dinilai lamban dalam mengatasi berbagai masalah. Ia dilambangkan dengan kebo. Bila kebo bisa bicara, mungkin ia akan protes karena sebenarnya geraknya tak pernah selambat pemerintah negeri ini.
Soal kecerdasan sang walikota, ada banyak contoh pejabat dan politisi kita yang mengidap penyakit seperti itu. Seorang teman pernah bertanya, kenapa pejabat dan politisi yang dulu pernah kuliah di luar negeri dan bahkan mendapat penghargaan malah pernyataannya remuk begitu? Terhadap pertanyaan itu, saya kembali menghadirkan fiksi. �Mungkin syarat menjadi pejabat atau politisi negeri ini harus siap menjadi bodoh,� jawab saya.
(dimuat Koran Madura, edisi 20 Maret 2013)
Akhir-akhir ini saya memang kerap membayangkan sejumlah kejadian memilukan di negeri ini sebagai sebuah fiksi. Sebagai fiksi, tentu saja ia hanya rekaan pikiran, tak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan. Persis dongeng-dongeng pengantar tidur. Namun, lagi-lagi, dongeng kancil yang mencuri timun masih tampak lebih menarik ketimbang peristiwa-peristiwa tersebut.
Menghadirkannya sebagai fiksi merupakan salah satu upaya menenteramkan hati dari gempuran berita-berita negatif yang diproduksi media setiap hari. Sebagaimana kita tahu, negeri ini dikelola dengan keributan yang sungguh luar biasa. Oleh para penguasa, kita dibuat pusing terhadap berbagai masalah yang tumpang-tindih. Tak usai masalah yang satu, timbul masalah berikutnya. Kasus yang satu diungkap untuk menutupi kasus-kasus lainnya.
Bosan dengan skenario politik yang mudah ditebak, akhirnya saya hanya berharap kepada dunia fiksi. Dunia tersebut menawarkan relaksasi. Ia kadang juga diam-diam membuat saya tersenyum, membayangkan betapa bodohnya saya saat mempercayai omongan politisi yang mengaku agamis, padahal maling.
Di waktu yang lain, Luis Sepulveda, novelis dan jurnalis kelahiran Cile tahun 1949, membawa ingatan saya kepada salah satu adegan dalam novelnya yang berjudul �Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta� (Marjin Kiri, 2005). Dalam novel tersebut digambarkan seorang walikota yang tambun dan malas berpikir. Penduduk El-Idilio menjuluki lelaki tersebut dengan la Babosa, Siput Lendir. Tubuh gempalnya terus memproduksi keringat dan membuat lelaki itu tak lepas dari pekerjaan memeras sapu tangannya.
Suatu ketika, walikota tersebut menuduh sejumlah orang Indian Shuar, penduduk lokal, menghunjamkan parang ke tubuh seorang bule yang datang ke daerah itu, hingga membuatnya tewas dan membusuk. Orang Shuar menolak, namun walikota ngotot dan menghantamkan popor senapannya. Antonio Jose Bolivar Proano, seorang pendatang dari San Luis, sebuah desa dekat gunung api Imbabura, mencoba menentang walikota. �Maaf. Anda omong kosong. Tak ada luka parang,� katanya. �Aku tahu apa yang kulihat,� sergah walikota. �Tidakkah Anda lihat daging terkoyak mengelupas? Tidakkah Anda lihat luka tetak ini dalam di bagian rahang dan makin ke bawah makin dangkal? Tidakkah Anda lihat ada empat sabetan, bukan satu?� lanjut Bolivar. �Apa maksudmu?� tanya walikota. �Tidak ada yang namanya parang empat mata. Ini bekas cakar. Cakar macan kumbang. Hewan yang sudah dewasa benar yang membunuhnya. Enduslah ini,� kata Bolivar.
Gambaran fisik sang walikota yang tambun bisa jadi sebuah simbol penguasa yang lamban. Negeri ini juga pernah menghadirkan sebuah simbol untuk pemerintah karena dinilai lamban dalam mengatasi berbagai masalah. Ia dilambangkan dengan kebo. Bila kebo bisa bicara, mungkin ia akan protes karena sebenarnya geraknya tak pernah selambat pemerintah negeri ini.
Soal kecerdasan sang walikota, ada banyak contoh pejabat dan politisi kita yang mengidap penyakit seperti itu. Seorang teman pernah bertanya, kenapa pejabat dan politisi yang dulu pernah kuliah di luar negeri dan bahkan mendapat penghargaan malah pernyataannya remuk begitu? Terhadap pertanyaan itu, saya kembali menghadirkan fiksi. �Mungkin syarat menjadi pejabat atau politisi negeri ini harus siap menjadi bodoh,� jawab saya.
(dimuat Koran Madura, edisi 20 Maret 2013)

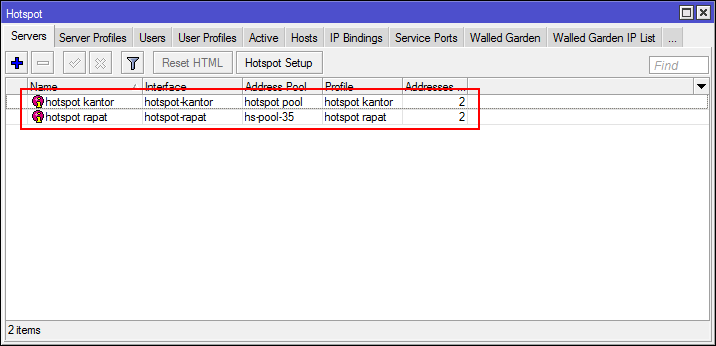

Comments
Post a Comment
-Berkomentarlah yang baik dan rapi.
-Menggunakan link aktif akan dihapus.